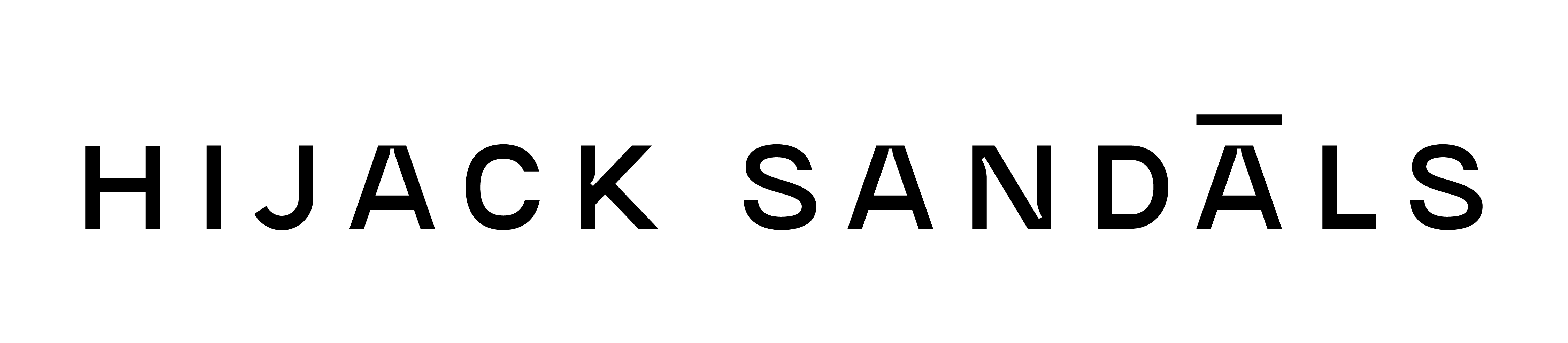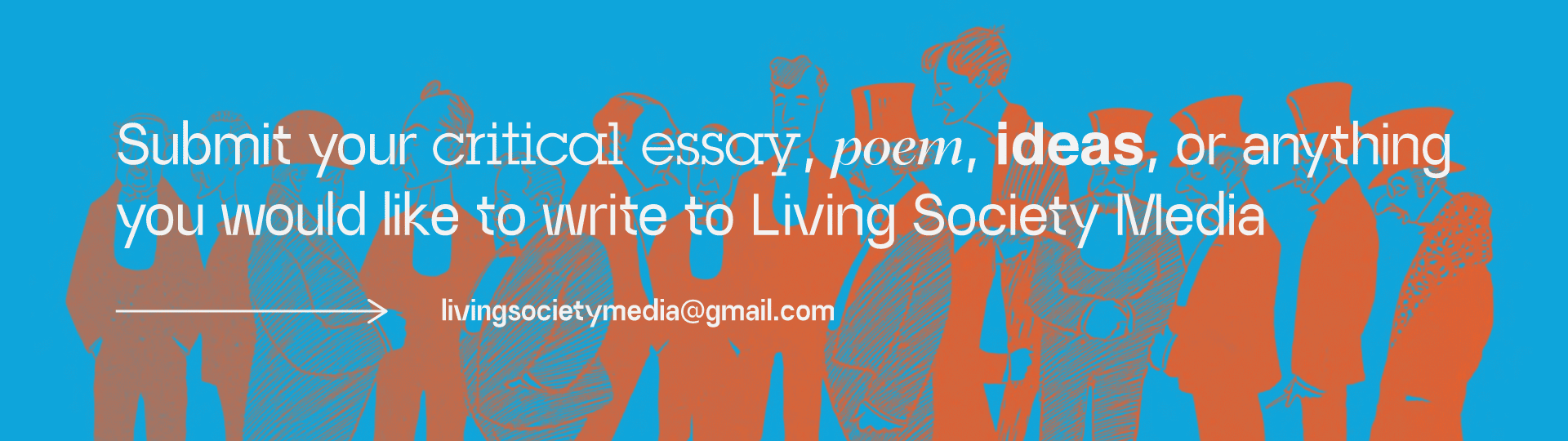Column
Informasi dan Bagaimana Selera Budaya Kita Terbentuk

Ditulis oleh Kelana Ashil Siddhawira
Mungkin tulisan ini akan diawali dengan pernyataan klise, bahwa teknologi telah membawa manusia ke kehidupan yang belum pernah terjamah sebelumnya, termasuk dari segi informatika. Sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama sekalipun menjadi terdisrupsi di tengah pusaran informasi yang kian hari kian kencang. Dampaknya? dapat dirasakan dari yang terbesar hingga terkecil. Akses yang disediakan internet untuk mengonsumsi tulisan, suara, serta tayangan nyatanya membentuk identitas diri, preferensi, juga selera kita.
Ngomong-ngomong teknologi, mungkin kamu pernah mendengar ungkapan “the medium is the message”, Marshall McLuhan lah tokoh yang bertanggung jawab atas tercetusnya kalimat tersebut. Menariknya, beliau dapat meramal bagaimana pola konsumsi informasi kita hari ini dibentuk puluhan tahun sebelum munculnya internet. Yah, lagi-lagi internet.
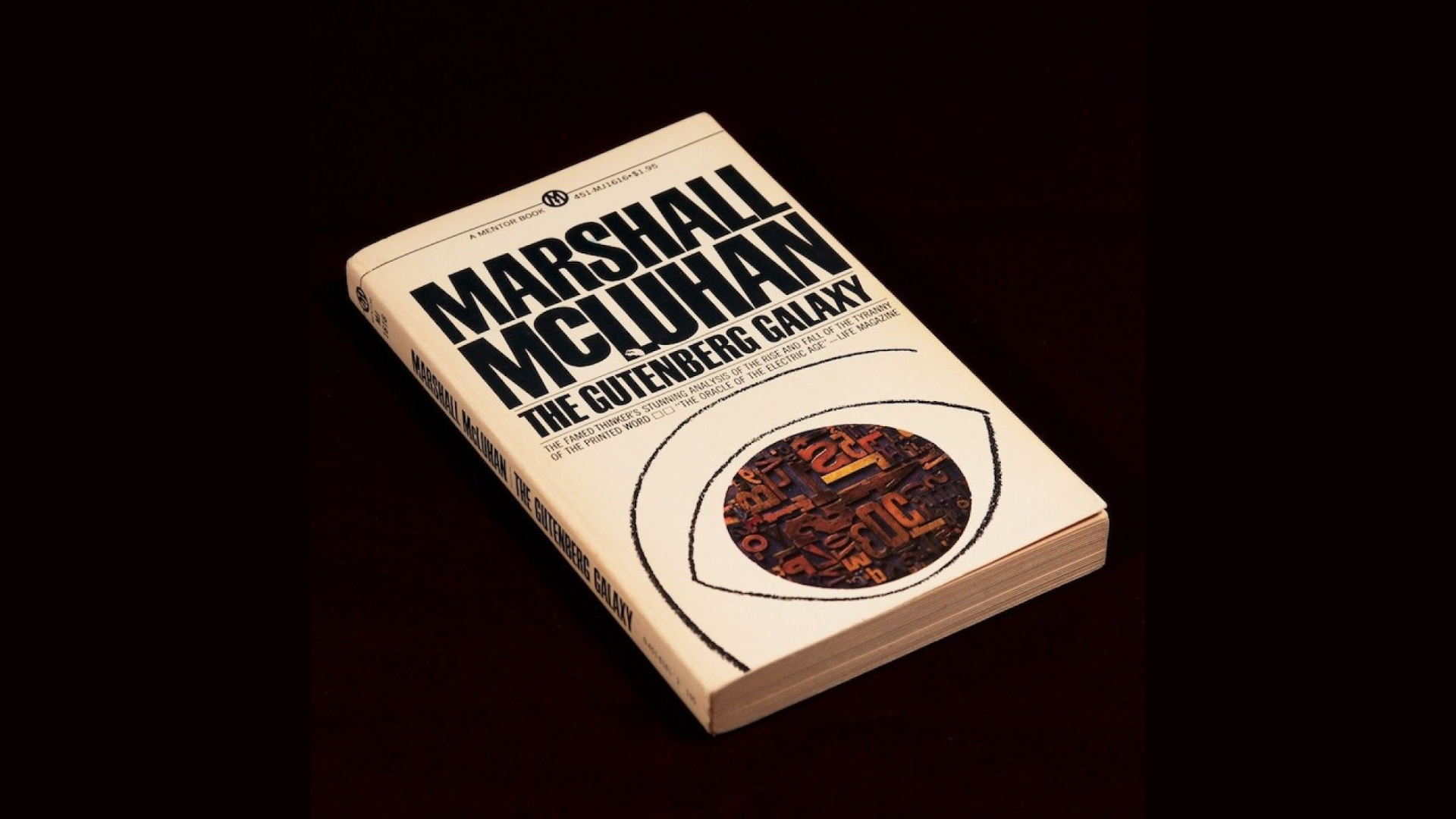
Image by: community.fansshare.com
Melalui bukunya, The Gutenberg Galaxy yang terbit tahun 1963, McLuhan mengatakan dunia akan menjadi semakin terhubung berkat adanya penyebaran perkembangan media di berbagai tempat. Dari situ, kemudian terbentuklah identitas kolektif internasional yang Ia sebut sebagai Global Village. Artinya, konsumsi media dan informasi di era ini akan lebih meng-global dibandingkan periode sebelumnya.
Masalahnya, Marshall McLuhan mungkin akan kaget juga jika meninjau bagaimana internet benar-benar membuat dunia bergerak semakin cepat saat ini. Tidak percaya? coba lihat pemerintah yang gencar-gencarnya membangun Ibu Kota Nusantara dengan semarak Metaverse. Bahkan, nasib kita sebagai masyarakat ditentukan oleh “Big Data” yang publikasinya dipertanyakan dalam rangka memilih pemimpin negara (#MaafTibaTibaPolitik #TBL). Jika menilik 10 tahun ke belakang, sebagian besar dari kita bisa jadi tidak terpikir untuk hadir di fase peradaban ini.
Rasanya, salah satu hasil dari derasnya arus informasi saat ini yang semakin sulit untuk di-filter, kita dihadapkan dengan berbagai situasi-situasi random sebagaimana yang saya contohkan di paragraf sebelumnya. Selera dan preferensi kita pun bukan pengecualian. Pertanyaannya, kok bisa sih seleraku yang maha dahsyat super duper ultra keren dipengaruhi oleh lalu lintas informasi di kanal-kanal media yang aku konsumsi? Dan kok bisa seleraku disebut random?
Jawabannya, teman-teman, ternyata sudah ditulis oleh banyak figur bahkan di abad 18. Namun, kita perlu memahami suatu konsep yang disebut sebagai keindahan (beauty). David Hume dalam bukunya yang berjudul Of the Standard of Taste (1757) menerangkan, hal yang kita anggap sebagai keindahan nyatanya tidak pernah muncul dalam objek itu sendiri. Lebih lanjut, Hume mengatakan bahwa keindahan hanya terletak di pikiran tiap individu.
Okay, sejauh ini kita memahami tulisan dari David Hume bahwa seseorang akan mempersepsikan yang menurutnya indah untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, menjadi wajar bila orang lain memiliki pandangan yang berbeda tentang apa itu keindahan dengan individu-individu lainnya. Bagi Hume, keputusan ini sepenuhnya berlandaskan perasaan yang tidak melewati proses kognitif.

Image by: sott.net
Dalam sisi bersebrangan, Alexander Baumganter yang hidup di era yang sama dengan Hume, memiliki pemahaman bahwa keindahan diproses secara kognitif dan saintifik. Indra sensori kita menjadi agen untuk mentranslasikan informasi dari pandangan serta pendengaran sebagai sesuatu yang kemudian Baumganter sebut “estetika”.
Immanuel Kant sama pentingnya dengan beliau-beliau yang sudah disebutkan sebelumnya. Ia menjadi penengah antara pandangan David Hume dan Baumganter. Kant, mengatakan ada dua hal yang bisa dikatakan indah dan memenuhi selera kita. Pertama, hal-hal yang tidak terkonsep (free beauty) seperti musik bising atau lukisan abstrak. Kedua, adalah keindahan yang terkonsep di dalam pikiran kita (adherent beauty), selayaknya patung Garuda Wisnu Kencana.
Dalam pandangan yang lebih krits dan modern, hadirlah Bourdieu yang beranggapan bahwa selera akan keindahan merupakan refleksi dari hirarki sosial. Menurutnya, selera di masyarakat “dibentuk” oleh kelas sosial yang lebih dominan guna memisahkan mereka dengan kelas-kelas lainnya. Dengan begitu, terdapat kecenderungan untuk seolah-olah merendahkan selera yang tidak umum di masyarakat.
Sebenarnya, saya mencoba agar tidak terlalu banyak memunculkan banyak tokoh (dan nampaknya saya gagal hahaha). Namun, dari pandangan yang berbeda-beda ini saya menangkap satu hal yang menjadi garis merah, yakni selera bergantung pada bagaimana informasi bergerak di sekitar dan cara kita mencernanya. Apapun perspektifnya.
Kalau mau pakai sudut pandang ekonomi nih, suplai informasi yang kita terima kemudian memunculkan “demand” terhadap informasi tersebut kemudian membentuk pertimbangan terhadap hal yang kita anggap indah, yaitu selera kita. Misal, semakin sering kita baca buku novel, semakin terbentuk juga parameter dalam pikiran kita yang mendefinisikan “novel bagus”. Dari sini, pencarian terhadap novel-novel bagus lainnya dimulai.
Nah ini juga nih yang bikin selera kamu beda dengan aku, atau orang-orang lain. Karena kekayaan atas informasi tertentu, pertimbangan akan kesukaan dan preferensi kita menjadi bias pada hal-hal tertentu pula. Bahkan, ini dapat terjadi di luar alam bawah sadar kita, dan menariknya sering dijumpai dalam trik-trik sulap.
Untuk mendukung paragraf di atas, terdapat artikel ilmiah ciptaan Rensink et al (2015) yang bereksperimen untuk menentukan pilihan responden dalam permainan kartu. Rekan pesulapnya, secara implisit menunjukan “target card” dengan cara melirikan kartu tersebut sebelum diacak. Hasilnya, dari 119 orang, 98% di antaranya memilih kartu yang sudah ditargetkan oleh pesulap.
Dari percobaan itu, kita akhirnya bisa mendapatkan pemahaman bahwa selera kita tidak sepenuhnya terbentuk secara subjektif atau berlandaskan perasaan semata. Stimulus dan respon berperan pula dalam menentukan apa yang menarik bagi mata serta telinga.
Sayangnya kalau kita lihat perputaran informasi saat ini, sebagaimana yang sudah dijabarkan pada awal tulisan, kita tidak dapat menggunakan kacamata yang sesederhana itu. Pertanyaan mengapa preferensi kita terhadap beberapa hal menjadi random masih belum terjawab.

Saya coba ambil contoh, pernah ga sih kalian ditanya “selera musik kamu apa?” dan bingung untuk jawab pertanyaan tersebut? Hipotesis saya, hal ini disebabkan oleh derasnya arus informasi yang kita terima dalam jangka waktu yang singkat. Sederhananya, frasa “too much information” memang sebuah kondisi yang nyata. Hasilnya adalah ketidakmampuan kita dalam menentukan atau memutuskan sesuatu.
Namun, ketika kita menjadi bingung terhadap persepsi tentang keindahan, atau dalam kata lain selera, menurut saya ini membuktikan ramalan dari Marshall McLuhan bahwa manusia sudah ada dalam lingkup sosial yang lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Artinya, kita tidak lagi mengasosiasikan diri hanya pada satu ketertarikan saja. Kita menjadi bagian dari kelompok-kelompok masyarakat yang bahkan belum pernah kita temui secara nyata. Atau yang McLuhan sebut sebagai Global Village. Ini semua berkat informasi.
Jadi, preferensi atau selera kita sebenarnya tidak serandom itu juga. Kalau misalkan kamu membedah satu-per-satu sumber informasi yang kamu konsumsi, persoalan tentang selera menjadi lebih less complicated. Termasuk pada diskursus yang mungkin akan terus ada sampai matahari muncul dari ufuk barat, “apakah seni dapat dinilai secara objektif?”. Menurut saya, jawabannya adalah bisa. Salah satu caranya adalah dengan menilai bagaimana seniman tersebut memanipulasi atau memodifikasi preferensi informasi bagi dirinya.
Kalau saya menggunakan paradigma yang (agak) kritis, informasi juga dapat mengaburkan atau bahkan memperjelas kelas-kelas sosial di masyarakat. Misalnya, ngabers yang hobinya gatekeeping sering merasa eksklusif dengan pengetahuan yang dimilikinya. Seolah yang bukan lingkar pergaulannya lebih inferior. Kocaknya kalau diajak diskusi juga gamau (#aneh).
Tapi sebaliknya, informasi bisa menjadi bekal untuk menyebarkan pengetahuan dan tempat yang kita tinggali jauh dari kesenjangan. Termasuk perihal selera. Ketika kita memiliki ketertarikan terhadap sesuatu, alangkah baiknya kita ramah untuk bagi kepada orang-orang yang awam dan merasa asing dengan hal tersebut.
Sebagai kesimpulan, saya akan menegaskan bahwa kita dapat menganggap diri kita sendiri sebagai kumpulan informasi. Situasi dan kondisi yang kita jalani saat ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh informasi yang dikonsumsi. Misalnya, kalau kamu lagi bingung, mungkin kamu terlalu banyak atau bahkan kurang mendapatkan informasi.
Kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih baik, termasuk dalam hal selera, kelilingilah diri kamu dengan informasi yang baik pula.
Referensi
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge. ISBN 0-415-04546-0.
Critique of the Power of Judgment (The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant), ed. Paul Guyer, trans. Paul Guyer and Eric Matthews, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Hume, D. (2017). Of the standard of taste. In Aesthetics (pp. 483-488). Routledge.
Olson, Jay & Amlani, Alym & Raz, Amir & Rensink, Ronald. (2015). Influencing choice without awareness. Consciousness and cognition. 37. 225-236. 10.1016/j.concog.2015.01.004.